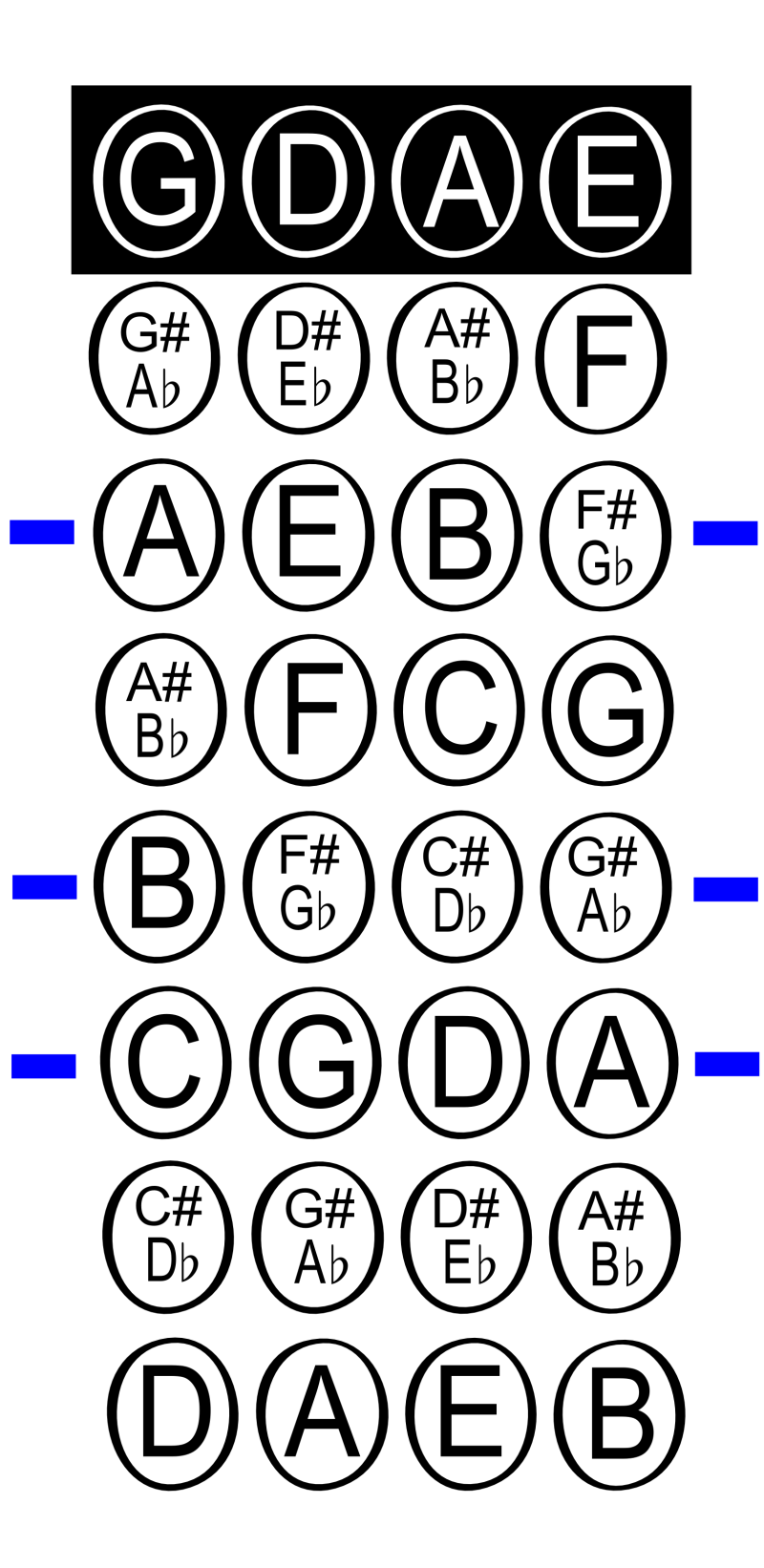Amaryllis
Bahkan, ketika aku melamun tentang
sebuah bintang yang tak kukenal pun, aku sempat teringat akan kau. Aku
tidak sedang bicara tentang cinta karena setiap perjumpaan kita bukanlah untuk berkencan
mesra. Terakhir kali aku melihatmu, kau tengah menghembuskan napas ke lensa
kacamata persegimu, membuatnya berembun, lalu mengelapnya dengan ujung bawah
kemejamu yang memang tak pernah kau masukkan dengan rapi. Kau tahu? Karena kau
melakukannya aku menjadi seperti ini. Aku membencimu dan ini justru membuatku tidak
bisa melupakanmu. Aku muak mengingatmu dan memutuskan untuk tak akan bisa
berhenti membencimu sejak saat itu, saat di mana kau membuatku tak mampu bermain
piano lagi.
"Dira? Kau di kamar, sayang?"
tiba-tiba terdengar suara lembut dari luar pintu kamar pribadiku. Itu suara ibu.
Ibuku yang wajahnya selalu berhiaskan senyuman meski aku tak pernah produktif
memberinya hal yang membanggakan. Wajah itu, wajah yang sama, yang sudah sejak
lama sekali tak berani kutatap lama-lama karena hanya melirik sekilas saja
sudah dapat membuatku menangis seharian. Dan aku tidak boleh menangis, terutama
di depannya. Aku tidak ingin melihatnya menangis diam-iam, tangis tanpa suara
yang mengiris dan berdurasi jauh lebih lama daripada tangisanku sendiri, serta
dapat membunuhku pelan-pelan.
"Dira... Nadira anak ibu yang
cantik. Bubur kacangnya sudah siap. Bagaimana kalau kita makan bersama di
balkon kamarmu? Sepertinya pemandangan sore ini sangat asyik untuk dilihat,"
katanya lembut, tetapi tampak sangat membosankan bagiku. Aku bosan dengan
kebaikannya, aku bosan dilayani oleh orang yang seharusnya kini aku layani dan
patuhi.
Ia membuka gorden kamarku, lalu
menggeser pintu kaca, mempersilahkan angin-angin senja nan sejuk meniup
seantero kamarku yang nyaris tidak lagi tampak hidup sejak dua bulan yang lalu.
Samar-samar mentari senja menebarkan sinar jingganya, yang membuat mataku
memincing dan menyipit sesekali karena belum siap merespon efek silau yang
ditebarkannya. Ibu sudah hampir menuntun kursi rodaku ke luar balkon, saat
tiba-tiba aku melihat sosok Nyonya Lily melewati jalan blok, di mana dari sana
balkon rumahku dapat terlihat dengan jelas.
"Ibu! Aku tidak bilang aku
ingin makan di sana. Kalau ibu mau mengapa bukan ibu sendiri saja yang
makan di sana? Lagipula, aku sangat benci dengan balkon itu. Mereka selalu saja
menoleh ke sini setiap melewati jalan itu," ucapku sedikit keras hingga
membuat bergetar gelas yang ibu parkir di atas piano putih di kamarku.
"Baiklah, nak, jika maumu
begitu. Kita makan di sini saja ya," kata ibu lembut dan iakhiri dengan
senyuman indah menenangakan yang sampai kapan pun mungkin tak akan pernah bisa
kutirukan. Aku malu. Perlahan dapat kurasakan panas mengaliri wajahku.
Sepertinya, lagi-lagi aku telah memuntahkan amarah berlebihan untuk hal, yang
mungkin menurut orang-orang sangat sepele. Sepele? Ini adalah aib bagiku!
Aku tak suka mereka memandangku
dengan aneh. Aku tak suka mereka membicarakan keadaanku dan membandingkanku
dengan aku yang dulu. Aku benci orang-orang yang selalu saja melihatku dengan kasihan,
tapi sedetik kemuian membicarakan hal-hal bodoh tentangku yang sudah pasti dikarang
bebas karena mereka tidak tahu apa pun tentang apa yang terjadi padaku, tentang
penderitaan yang kurasakan dua bulan terakhir ini. Dasar pengecut sakit jiwa! Mereka
mengeroyokku dalam diam. Bahkan, Cinderella pun hanya disiksa oleh tiga orang!
"Dira? Makan dulu, nak? Hari
ini Ibu akan menyuapimu, ya. Aaa..."
Mulutku tak bergeming.
"Mengapa, Dira?"
Aku diam. Aku tak tahu mengapa
egoku sebesar Gunung Fuji.
"Dira? Kamu marah pada
ibu?" tanyanya. Suaranya melemah. Aku tak berani memandanganya karena aku
tahu sekarang matanya sedang berkaca-kaca. Ibu, beri aku waktu.
"Dira?"
"Tinggalkan aku, Ibu! Aku bisa
makan sendiri! Aku bukan bayi! Dan aku masih punya kaki!" teriakku. Kali
ini aku dapat melihat dari sudut mata kananku, air dalam gelas itu bergoyang
akibat ulahku, menaikkan suaraku. Begitu pula dengan ibu, bibir dan tangannya
gemetaran, meskipun ia menyembunyikannya dengan senyuman dan remasan tangan. 'Ibu
maafkan aku, aku tak pernah bermaksud untuk membentakmu. Namun, tolong
percayalah bahwa aku bukan orang cacat yang menyedihkan. Aku bisa seperti yang
lain!'
"Baiklah, sayang. Ibu ke dapur
dulu, ya."
Kau percaya? Hei, kau dasar
kacamata kuda! Bahkan ia tersenyum saat aku sudah membentak dan bicara degnan
sangat kasar padanya. Ini semua gara-gara kau. Kalau kau tak mematahkan
jari-jari tanganku, mungkin ibuku tak akan menderita setiap hari olehku dan oleh
tetangga-tetangga menyebalkan itu! Tunggu pembalasanku, kau bocah tengik!
Aku mengalihkan pandanganku dari
pintu kamarku, sembari memastikan ibu betul-betul telah meninggalkan kamarku,
menuju sebongkah piano yang terparkir di dekat pintu balkon. Tubuh piano itu tidak
lagi tampak putih karena terselimuti oleh debu. Kau memang telah mematahkan
jariku, tapi kau tidak bisa mematahkan ambisiku untuk "menang" darimu
karena aku memang lebih baik darimu dan satu-satunya yang terbaik di sekolah.
Aku tidak akan mati jika aku bermain piano dengan jari-jari kakiku yang cukup
panjang ini. Aku akan membuktikan bahwa aku akan selalu lebih baik darimu, Tuan
Muda Hide yang memuakkan!
*****
Sial! Aku sudah berkali-kali
berlatih, tapi aku masih saja belum terbiasa. Aku akan berusaha untuk menekan tuts
ini lebih keras, meskipun kelingking kaki kiriku masih terlalu lemah. Jika
seperti ini terus aku tidak akan bisa memainkan tempo dengan baik. Tampaknya,
aku tidak akan dapat memainkan lagu Chopin dalam sekejap seperti dulu lagi. Ah!
Hide! Kau benar-benar harus membayarnya!
Pergerakanku masih sangat kaku. Aku
tidak mungkin mengikuti kontes piano dengan hanya memainkan lagu Twinkle
Twinkle. ‘Oke Dira! Kau pasti bisa!
Selagi ibu pergi, manfaatkan waktumu dengan sebaik-baiknya untuk berlatih.’
Mungkin aku harus benar-benar memulai dari pemanasan lagi. Jari-jari dan
pundakku mulai pegal. Wah! Tak kusangka tangan doraemon ini berguna juga
untuk memijit bahu? Tuhan, Kau memang selalu menawan dengan segala kejutan
indah-Mu.
Tok...tok...tok. Suara pintu? Ibu? Ini gawat, kalau sapai dia tahu apa yang
sedang aku lakukan. Di mana? Di mana novel milik bocah sialan itu? Mengapa
kamar ini jadi begitu berantakkan? Payah ini! Ibu masih belum boleh tahu
tentang ini, sekarang. Di mana novel sialan itu? Nah ketemu kau! Bantu aku
mengelabui ibuku. Baca, baca, baca!
"Dira, ibu masuk."
*****
"Kontes piano? Hah! Ibu ingin
mereka menertawakanku? Lagipula aku sudah lupa bagaiamana cara bermain
piano!" Demi Menara Tokyo! Aku kaget sekali dengan ajakan ibu untuk
mengikuti kontes piano. Bagaiamana ibu tahu kalau aku mulai berlatih piano
lagi?
"Dira..." Ya, ampun!
Benarkah ibu sedang menangis? Tuhan, tolong hukum aku. Apakah aku sudah sangat
menyakiti hatinya? Maafkan aku Tuhan, aku tak bermaksud melakukan hal buruk
kepadanya.
"Dira. Ibu tidak pernah tahu
kalau kau masih sangat menyukai piano. Hiks. Maafkan ibu untuk ketidakpekaan
ibu. Hingga kemarin ibu tak sengaja mendengarkan permainan pianomu, sangat
cantik. Ibu di belakangmu dan akan selalu mendukungmu. Kau tak perlu
mencemaskan apalagi mempedulikan apa kata tetangga, paman, bibi dan kakek.
Kejarlah mimpimu, nak," kata ibu masih sambil menangis sesenggukan.
Apa yang harus kulakukan, Tuhan? Ia
pasti sedih kalau tahu tujuanku bermain piano lagi adalah untuk mengalahkan
Hide.
*****
Bagus! Gerakanku sudah lebih baik!
Aku harus menentukan lagu yang tepat dengan kondisiku saat ini. Lagu apa yang
tepat untukku dan tidak akan bisa dimainkan oleh Hide? Hide itu... Ia tidak
pernah mau memainkan lagu bertempo lambat bukan? Shymphoni 7 Beethoven? Atau
Schubert? Mozart? Ia pasti memilih lagu Chopin favoritku! Demi bunga sakura aku
belum pernah sebingung ini dalam memilih lagu.
Halo, Tuhan! Aku mulai terbiasa
dengan tangan doraemon dan jari kaki menariku. Biarkan mereka bermain harmonis
hingga tiba hari kontes nanti, Tuhan. Hei, bunga amarilis! Kau cerah sekali
hari ini. Apakah kau ingin membalas dendam kepada bunga lili di sampingmu
karena ia mekar lebih dulu darimu dan sekarang malah mulai keriput dan layu,
meninggalkanmu mekar sendirian? Ahaha. Kau terlalu cantik untuk mambalas
dendam, amarilis sayang.
Amarilis? Amaryllis? Mengapa tak
pernah terpikirkan sebelumnya??? Bingo!!! Amaryliis! Hide sangat membenci lagu
itu!
*****
"Ibu yakin, ibu mendaftarkanku
di kontes yang sama dengan kontes yang Hide ikuti?" Ibu mengangguk,
matanya memandang ke arah sejumput ilalang kering yang tumbuh di taman yang
sedang kami lewati ini. Aneh, ia tidak memandangku saat mengiyakanku. Ah
biarlah, aku harus berkonsentrasi pada kontesku.
Langit hari ini begitu cerah. Biru
muda tergelar di mana-mana. Hitam putih tuts piano itu bahkan turut berubah
warna menjadi biru dan putih. Sungguh damaianya hati ini. Aku sebenarnya tak
ingin menang dari Hide, aku hanya ingin membuatnya merasa bersalah, menangis,
meminta maaf dan mengakui kemampuanku di depan banyak orang dan penikmat musik.
Aku tahu jika sebenarnya... ia baik.
Benar. Ia baik. Namun, mengapa ia
tak segera menemuiku setelah kejadian itu? Mengapa ia tidak menolongku saat aku
terjatuh dan kedua tanganku terlindas mobil ayahnya? Apakah kita benar-benar
tidak pernah berteman? Apakah selama ini ia hanya menganggapku sebagai seorang
saingan? Tuan Muda Hide, si Beethoven Jepang? Kalau ia Beethoven maka aku Chopin!
Bagaimana mungkin si pemain piano ceroboh yang tidak peka saat dipanggil seperti
ia bisa dijuluki Beethoven? Nama julukan itu terlalu baik untuknya.
Benar juga! Jika kuingat-ingat, ia
sangat menyebalkan ketika berhadapan dengan piano. Ia tidak akan menengok ke
mana pun, tidak akan tersenyum, tidak merespon ketika kupanggil sekali pun. Apa
karena dia sombong? Atau memang benar karena pengaruh scence musik
dan konsentrasinya yang sangat baik saat menikmati permainnya sendiri sehingga ia
sangat susah untuk berpaling dari piano di hadapannya. Ya, ampun aku harus
fokus pada permainanku nanti. Sekarang saatnya senam jari! Pemanasan.
Ruangan backstage sudah
sangat ramai oleh peserta. Aku kembali hidup! Namun, tunggu! Mengapa orang-orang
seperti mereka ada di sini? Mereka aneh. Gadis ini, ia hanya memiliki empat
jari tangan. Kakak laki-laki itu, ia tak punya kaki? Tempat apa ini? Ibu?
Ibuku? Ia tega membuangku ke kontes murahan seperti ini?
"Ibu, maksud Ibu apa membawaku
ke tempat seperti ini? Aku tidak seperti mereka ibu. Aku jenius musik. Aku
tidak cacat! Aku hanya tak punya jari gara-gara Hide! Ibu, aku kece..."
"Hai, Nadira. Ohisashibure
desu ne?" suara ini tak asing dan sepertinya asalnya dari
belakangku.
Laki-laki berkacamata hitam? Cuih!
Ia datang juga, Hide? Berubah dan semakin bergaya ia sekarang? Kacamata hitam?
Digandeng gadis cantik dan sangat muda? Tak kusangka ia berubah sedrastis itu
hanya dalam waktu setahun. Ia bahkan tak berhenti tersenyum, seperti ibu. Senyum
yang memuakkan. Ya, kalian sama-sama sangat memuakkan.
"Baik atau buruk kabarku,
bukan urusanmu! Kau yang menyuruh ibuku membujukku untuk mengikuti kontes
memalukan ini? Cuih! Tak cukup kau menghancurkan mimpiku?" Napasku
tersengal. Aku tak mampu menatap wajah ibuku. Entahlah apa yang kulakukan, aku
tak tahu apakah aku sedang menuduh, memfitnah atau memotong hati seseorang. Aku
benci dibohongi, apalagi oleh ibuku sendiri.
Sial! Mengapa orang ini tidak
meresponku? Setidak penting itu kah pertanyaanku? Apakah ia tak punya hati,
sampai-sampai tak tahu caranya meminta maaf padaku? Oke, kalau ini maumu,
melihatku disaksikan orang-orang dalam kontes piano untuk penyandang cacat.
Oke! Kau tahu, Hide? Hatimu juga cacat! Lalu, mengapa kau tidak mengikuti
kontes ini juga?
"Kontestan selanjutnya, Hide
Ninomiya..." suara tepukan tangan dari arah bangku penonton terdengar
keras siap menyambut kontestan selanjutnya, yang ternyata adalah Hide.
"Kakak, sekarang giliranmu
tampil," kata gadis cantik yang menggandeng Hide. Ia pun mengantarkan Hide
hingga ke atas panggung. Mereka berdua tampak sangat serasi. Apakah mereka akan
berduet? Pamer sekali. Namun, gadis itu memanggil Kakak? Ia adik perempuan Hide
yang selama ini ia ceritakan? Cantik sekali.
Nadira! Fokus! Musuh besarmu sedang
menebar pesona di atas panggung sebagai kon... kontestan? Ia kontestan?
Sandiwara macam apa ini? Sungguh aku tak mengerti lagi mengapa Hide yang
sekarang semakin pandai berakting. Ia bukan lagi Hide si kacamata kuda, tapi
Hide si tidak tahu malu!
Gadis itu masih melingkarkan gandengan
tangannya di lengan atas Hide. Mereka membungkuk bersama ke penonton lalu
berjalan ke arah tempat duduk. Hide duduk di kursi piano yang telah disediakan
oleh panitia, lalu gadis itu meninggalkannya sendiri. Gadis itu...maksudku adiknya
itu... tidak bermain dengannya? Mereka tidak berduet?
Perlahan, Hide mulai memainkan jarinya,
memainkan tuts-tuts piano di hadapannya dan menghasilkan rangkaian nada sangat
kukenal. Apa ini? Amaryllis? Hide memainkan Amaryllis? Mengapa? Mengapa ia
memainkan lagu yang dibencinya? Mengapa ia tidak lagi membenci lagu yang
kusukai? Mengapa ia memainkan lagu yang terakhir kali ibunya mainkan sebagai
pengantar tidur untuknya, sebelum mencampakan ia dan adiknya di keesokan paginya?
"Hallo, Kak,” sapa gadis yang
selalu menggandeng Hide sedari aku bertemu dengannya. “Kau Kak Nadira? Kau
teman kakakku, kan?" gadis cantik itu kembali menyapaku. Amaryllis
mengalun dengan pasti. Temponya dimainkan dengan lambat, jauh lebih lambat dari
tempo asli hasil komposisi Henri Ghys. Setiap nada yang dimainkannya seolah
diisi oleh napas pemainnya. Hide memainkan perasaannya. Ia menambahkan banyak
sekali bumbu dan hiasan dalam sajian Amaryllis. Sampai-sampai tidak ada sedikit
pun celah kekosongan dalam permainannya yang tidak isi dengan perasaannya. Aku terbawa
ke dalam permainannya, ke dalam dunia imajinasi yang berhias bunga-bunga dan
mentari musim semi, membuatku hampir lupa akan kehadiran gadis cantik yang
menyapaku.
"Iya. Aku Nadira. Kau
adiknya?" Aku bertanya balik kepada gadis itu.
"Iya. Perkenalkan namaku
Nagisha. Yoroshiku onegaishimasu," jawabnya dengan sangat
manis. Amaryllis masi berbunyi, nada-nadanya seolah berkilau dan menari di
batang-batang hitam putih yang tampak ikut meleleh. Hide...
"Nadira-san... Setahun
lalu..." dan kata-katanya itu seketika membuat pandanganku memburam.
*****
Dunia menggelap dan kenangan masa
lalu terputar kembali. Aku dan Hide baru saja pulang dari sekolah musik. Kami
berdua sama-sama dari kelas piano. Sore itu, kami berdua akan menonton konser Ryusuke
Honda. Kami hampir terlambat dan aku tidak mau melewatkan satu nada pun dari
permainan sang maestro pujaan. Aku berlari di sepanjang jalan menuju tempat
konser. Di belakangku, Hide mengejarku dengan kewalahan.
Aku sudah mencapai tepi jalan raya
dan mengantre bersama pejalan kaki yang akan menyeberang lainnya. Hide masih
sempoyongan berlari. Tiba-tiba, ia berhenti, lima meter sebelum tempat
penyeberangan. Ia melepas kacamatanya, meniupnya lalu ia mengelapnya.
Aku sangat marah saat itu dan
bersiap untuk menarik kerahnya untuk segera bergegas. Namun, tiba-tiba lampu
lalu lintas menyala merah. Orang-orang pun berbondong-bondong menyeberang. Aku
tidak siap dan tiba-tiba ada seorang bapak berbadan besar yang menabrakku
hingga aku jatuh tertelungkup ke arah jalan. Hide masih sibuk mengelap
kacamatanya tanpa sadar bahwa aku terjatuh.
Saat aku akan bangkit, tiba-tiba
sebuah sepeda motor menyerempet dan sekali lagi membuatku terjatuh. Naasnya,
saat itu ada sebuah mobil yang mulai melaju kembali karena lampu sudah menyala
hijau lagi. Aku tak mampu menghindar. Mobil itu menggilas pergelangan tangan
kananku dan lengan bawah tangan kiriku. Ban depan dan belakang tanpa kecuali.
Lalu semuanya gelap dan aku tidak pernah melihat Hide lagi saat itu.
Ibu memberitahuku bahwa ayah Hide
adalah pengemudi mobil yang menabrakku itu. Beliau merasa sangat bersalah dan
selalu rajin menjengukku, meski aku tidak pernah mau menemuainya. Namun tidak
dengan Hide. Ia menghilang. Aku sedih kehilangannya dan lama-lama benci, hingga
menjadi seperi ini.
*****
"Nadira-san. Kamu
tidak apa-apa?" suara Nagisha menyadarkanku.
"Iya. Tidak apa-apa,"
jawabku singkat.
"Kakakku... Ia menyusulmu ke
rumah sakit, setahun lalu. Ia sangat merasa bersalah dan menyesal. Ia sangat
menyayangimu dan menganggapmu sebagai sahabat, Nadira-san," napasku
tecekat.
"Namun, Tuhan berkehendak
lain. Sepertinya Ia sedang menguji kekuatan kakak. Motor yang kakak naiki
bertabrakan dengan motor lain di tikungan menuju rumah sakit tempatmu dirawat.
Ia terseret bersama motornya. Kakak tak menggunakan helm saat itu dan kacamata
kakak pecah. Mata kakak... matanya..." Nagisha diam sejenak aku panik, aku
menyesal.
"Mata kanannya tidak
terselamatkan sedangkan mata kirinya... ada serpihan kaca spion berukuran
sangat kecil yang masuk ke mata kirinya. Akibatnya, ia tidak dapat melihat
dengan baik dan ia selalu melihat tujuh bayangan benda dengan mata kirinya.
Kata dokter, itu adalah refleksi bayangan yang diakibatkan oleh kaca itu. Kakak
tak berani menemuimu. Akhirnya, kakak menyuruh sopir kami untuk berpura-pura
menjadi ayah kami dan menjengukmu setiap hari. Sopir itu berpura-pura menjadi
orang yang menabrakmu. Ia memberitahukan kabarmu setiap hari ke kakak. Kakak
sangat sedih karena Nadira-san... seperti ini. Pendengarannya pun
semakin terganggu dan bertambah parah dibandingkan dulu saat sebelum
kec..." aku tak bisa membendung air mataku. Ini seperti adegan film. Aku
tak bisa lagi diam mendengarkannya.
"Na... Nagisha-chan, ia
sekarang tak bisa mendengar dan sangat menderita dalam melihat? Selama ini, ia
mendapat julukan Beethoven Jepang itu, gara-gara pendengarannya yang kurang
itu?" Nagisha mengangguk. Aku pun melemas dan terjatuh. Ibu memelukku. Ia
menangis, tapi dari ekspresinya, sepertinya ia sudah mengetahui semua ini.
Tuhan, aku begitu... berhati jahat. Tuhan... bahagiakan Hide, aku mohon.
"Hnn... Nagisha-chan, tolong
bantu aku!" panggil seorang laki-laki bersuara baritone dari arah panggung. Ternyata Amaryllis telah selesai
dimainkan. Hide pun sudah membungkuk ke arah penonton yang dibalas dengan
tepukan tangan dan teriakan "Bravo" oleh sebagian dari mereka.
Aku tak tahan lagi, kutarik diriku
dari kejatuhan. Aku berlari menghambur ke arah Hide dan meraih tangannya.
Menuntun jemarinya ke arah tuts piano. Kunaikkan kakiku dan bersiap memijit
tuts-tuts piano. Kumainkan tiga bar awal Amaryllis. Kuajak ia berduet bersama.
Ia menyentuh jemari kakiku dan sudah tentu ia mampu menebak nada-nada yang
tengah kumainkan, meskipun ia tidak dapat mendengarkan permainanku.
"Amaryllis... Nadira, kaukah
itu? Kau suka dengan permainanku tadi? Amaryllis untukmu, Nadira. Kau
Amaryllisku, Dira. Kau menggantikan ibuku, Amaryllisku yang hilang. Maukah kau
memafkanku dan tak menghilang lagi?"
“Aku yang seharusnya menanyakan
itu, Hide. Maukah kau tak bersembunyi dariku lagi? Kau temanku bukan?” tanyaku.
Dia mengangguk. Kami pun tersenyum
bersama diiringi riuh rendah penonton yang turut berkaca-kaca dalam suka. Ini
bagaikan mimpi atau adegan dalam film lebih tepatnya... dapat berduet lagi
dengannya, sahabatku. Aku tak akan lagi menghilangkan diriku darimu, Hide. Tak
akan pernah, selamanya. Aku berjanji, Hide. Maafkan aku membuatmu seperti ini.